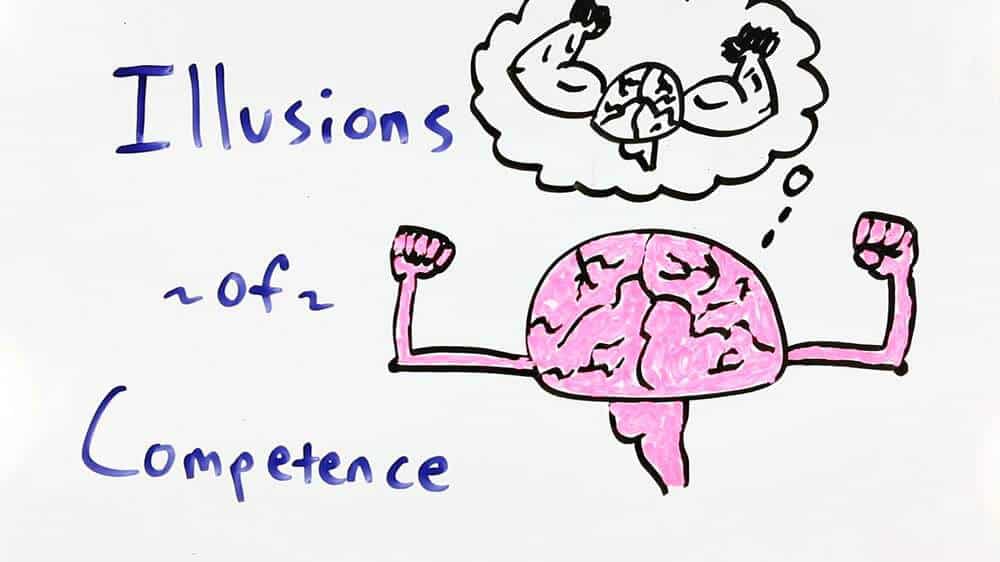Oleh: Anindito Aditomo
Salah satu ukuran utama kualitas sekolah dan sistem pendidikan adalah hasil belajar siswanya. Pengetahuan dan keterampilan apa yang diperoleh siswa dari proses belajar mengajar di sekolah? Jika siswa tidak bertambah pintar setelah sekian tahun menjalani proses belajar-mengajar, mutu sekolah tentu patut dipertanyakan.
Dalam hal ini, yang kerap mendapat perhatian adalah hasil belajar siswa secara keseluruhan (rata-rata). Contohnya adalah ranking mutu sistem pendidikan yang dibuat studi internasional seperti PISA atau TIMSS, atau ranking sekolah yang diumumkan Kemendikbud berdasarkan rata-rata skor Ujian Nasional. Yang juga sering diperhatikan adalah hasil belajar terbaik. Misalnya, siswa yang mendapat skor ujian tertinggi di sebuah sekolah atau daerah kerap masuk berita. Atau, banyak sekolah yang membanggakan jumlah siswanya yang berhasil meraih medali olimpiade atau lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri.
Problem kesenjangan
Yang lebih jarang dan sebenarnya juga amat penting diperhatikan adalah variasi dalam hasil belajar tersebut. Variasi hasil belajar ini bisa antar sekolah atau antar sektor pendidikan (misalnya, sekolah negeri vs. swasta, SMA vs. SMK, atau SMA vs. MAN). Variasi hasil belajar antar sekolah dan sektor pendidikan yang (terlalu) tinggi merupakan sebuah masalah.
Hal ini problematis karena mencerminkan kesenjangan dalam hal layanan yang diberikan oleh sekolah dan pemerintah. Idealnya, kualitas layanan publik bersifat merata. Mau sekolah di mana pun, siswa seharusnya mendapat guru, fasilitas, dan proses belajar yang baik.
Variasi juga bisa terjadi antar kelompok siswa (misalnya, etnis atau gender) dan antar kelompok masyarakat (misalnya, siswa dari keluarga kaya dan miskin). Variasi antar kelompok yang besar juga merupakan masalah. Kesenjangan antar kelompok ini disebut sebagai problem equity atau keadilan pendidikan, karena menunjukkan bahwa prestasi siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendalinya.
Misalkan prestasi sekolah siswa ditentukan oleh seberapa tinggi pendidikan ayah-ibunya atau seberapa baik fasilitas belajar yang ada di rumah. Ini problematis, karena siswa tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga kaya atau miskin. Karena itu, semakin besar kecilnya pengaruh latar belakang sosial-ekonomi terhadap prestasi akademik siswa dianggap sebagai indikator keadilan pendidikan.
Seberapa besarkah variasi atau kesenjangan antar sekolah dan kelompok masyarakat ini di Indonesia? Tulisan ini menyajikan perkiraan besarnya kesenjangan dalam hasil belajar pada siswa kelas 4 SD di Indonesia. Data yang saya gunakan berasal dari studi TIMSS 2015 yang mengukur penguasaan matematika dan sains (IPA). Agar lebih fokus, saya hanya membahas hasil belajar matematika saja.
Kesenjangan antar sekolah
Dalam TIMSS 2015, rata-rata skor siswa SD kelas 4 di Indonesia adalah sekitar 397, sedangkan rata-rata internasional adalah 500. Skor ini mencerminkan penguasaan matematika yang tergolong paling rendah secara internasional (setidaknya dibanding negara-negara peserta studi TIMSS 2015).
Sampel TIMSS 2015 di Indonesia mencarkup 230 sekolah dasar. Grafik (histogram) berikut memberi gambaran tentang variasi skor antar 230 SD tersebut.

Tampak bahwa terdapat rentang skor yang cukup besar. Di satu sisi (sebelah kanan histogram) ada sekolah yang siswanya secara rata-rata memiliki skor mendekati 600. Itu setara dengan skor rata-rata siswa di Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Di sisi lain (sebelah kiri histogram), ada sekolah yang skornya mendekati angka 200.
Kalau dihitung secara lebih cermat, skor matematika sekolah pada posisi 10% teratas adalah sekitar 466, sedangkan skor sekolah pada posisisi 10% terbawah adalah sekitar 300. Dengan kata lain, kesenjangan antara sekolah-sekolah paling top dan paling bawah di Indonesia adalah sekitar 166 poin. Ini mencerminkan kesenjangan mutu yang cukup besar. Sayangnya, informasi tentang lokasi sekolah tidak menjadi bagian dari data publik TIMSS, sehingga tidak mungkin mengetahui di mana kesenjangan tersebut terjadi.
Kesenjangan sosial-ekonomi
Kesenjangan sosial-ekonomi dalam pendidikan diukur dari seberapa erat kaitan antara status sosial-ekonomi (SES) dengan prestasi akademik siswa. Seperti disebutkan sebelumnya, kuatnya kaitan status sosial-ekonomi dengan prestasi akademik adalah indikator dari ketidakadilan sistem pendidikan.
Status sosial-ekonomi siswa dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan prestise pekerjaan orangtua. Status sosial-ekonomi juga bisa dilihat dari pendapatan dan sumberdaya finansial/material yang dimiliki keluarga. Dalam analisis berikut, saya hanya akan melihat data TIMSS tentang tingkat pendidikan orangtua dan sumberdaya keluarga yang dapat mendukung kegiatan belajar di rumah (buku dan akses internet).
Secara metodologis, kaitan SES dan prestasi belajar diukur menggunakan teknik statistik bernama regresi multijenjang atau multilevel. Teknik ini memungkinkan kita untuk memisahkan kaitan antar variabel pada level individu (siswa) dan kelompok (kelas atau sekolah). Tabel berikut menyajikan hasil regresi multijenjang data TIMSS 2015 untuk sampel Indonesia.
| Pendidikan ortu | Fasilitas belajar | |
| Antar siswa | 11,04 | 6,48 |
| Antar sekolah | 41,31 | 33,11 |
Angka yang ada di tabel adalah perbedaan skor antar kategori pendidikan ortu dan fasilitas belajar. TIMMS membagi pendidikan orangtua ke dalam lima kategori, mulai dari SD, SMP, SMA, diploma, dan sarjana (atau lebih tinggi). Pada level individu, skor matematika siswa yang orangtuanya berpendidikan sarjana secara rata-rata lebih tinggi 11 poin dibanding siswa (di sekolah yang sama) yang ortunya berpendidikan diploma. Jika yng dibandingkan adalah siswa yang ortunya berpendidikan sarjana vs. SD, maka selisihnya menjadi 11 x 4, alias sekitar 44 poin.
Pada level sekolah, kesenjangannya lebih besar lagi. Sekolah yang rata-rata siswanya memiliki ortu sarjana memiliki skor matematika yang 41 poin lebih tinggi dibanding sekolah yang rata-rata siswanya memiliki ortu lulusan diploma. Jika yang dibandingkan adalah sekolah dengan kategori tertinggi (ortu siswa kebanyakan sarjana) dan terendah (ortu siswa kebanyakan lulusan SD), selisih skornya adalah sekitar 160 poin. Ini hampir sama dengan kesenjangan antara sekolah terbaik dan terburuk di Indonesia (lihat bagian sebelumnya).
Meski tidak sekuat pendidikan orangtua, fasilitas belajar di rumah juga memiliki kaitan serupa dengan hasil belajar matematika siswa. Dalam hal ini, TIMSS membagi fasilitas belajar ke dalam tiga kategori: buruk, sedang, dan baik. Siswa yang memiliki buku dan koneksi internet pada kategori tertinggi, secara rata-rata juga memiliki skor matematika lebih tinggi 13 poin (6,5 x 2) dibanding mereka pada kategori terendah. Di level sekolah, selisihnya adalah sekitar 66 poin.
Penutup
Temuan di atas menunjukkan besarnya peran latar belakang keluarga pada prestasi di sekolah. Hal ini sebenarnya sudah cukup lama disadari, setidaknya sejak tahun 1960-an dengan terbitnya hasil penelitian di Amerika yang kemudian terkenal sebagai Coleman Report. Berita buruknya lagi, kesenjangan pendidikan antar kelas sosial-ekonomi tidak banyak berkurang setelah sekian dekade.
Apakah ini berarti sekolah gagal dalam mengatasi problem kesenjangan? Jawabannya tergantung dari perspektif mana kita melihat. Di satu sisi, kebanyakan sekolah memang terlihat tidak berhasil menutup kesenjangan. Tapi di sisi lain, riset menunjukkan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan guru dan sekolah untuk mengatasinya. Barangkali ini akan saya bahas di tulisan berikutnya.