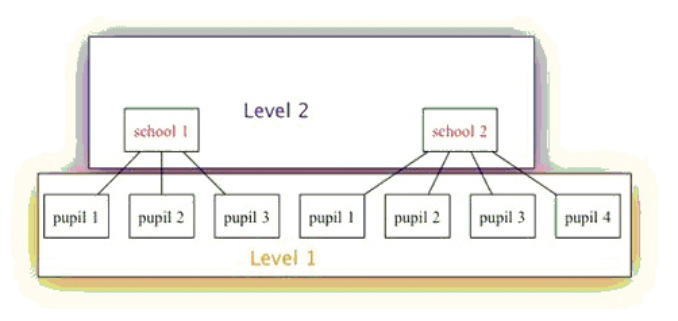) kita? Mengapa dua orang yang sama-sama punya common sense, bisa begitu berbeda pendapat dalam menilai benar-salahnya sebuah tindakan? Saya menjadi tertarik mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini semenjak Pilkada Jakarta kemarin.
Bagi saya, perdebatan tentang berbagai isu terkait Pilkada mencerminkan perbedaan mendasar dalam penilaian moral, alias apa yang seharusnya dianggap benar dan salah. Sebagian kalangan tersinggung dan merasa bahwa kalimat “Jangan mau dibohongi pakai al-Maidah” melanggar batas moral.
Sebagian lagi justru menilai ucapan tersebut sebagai tindakan bermoral karena menguak manipulasi agama untuk kepentingan politik. Sebagian kalangan merasa sah-sah saja mengancam tidak menyolatkan jenazah pendukung Ahok. Bagi yang lain, ancaman tersebut jelas melanggar nilai-nilai moral. Sebagian kalangan percaya bahwa memilih pemimpin non-Muslim melanggar moral agama. Sebagian yang lain justru percaya bahwa memilih Ahok adalah tindakan yang bermoral.
Dalam pertentangan moral semacam ini, dialog menjadi sulit bukan saja karena masing-masing pihak merasa benar. Dialog menjadi sulit juga karena masing-masing pihak benar-benar tidak bisa memahami perspektif lawannya. Mengapa demikian? Sebagian jawabannya dipaparkan Jonathan Haidt, seorang kampiun psikologi moral kontemporer, dalam bukunya “The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion”. Tulisan berikut menyarikan Bab 1 dari buku tersebut, ditambah bumbu dari beberapa sumber sekunder.
Nature vs. Nurture
Sebagaimana banyak pertanyaan mendasar tentang manusia, variasi jawaban tentang asal-usul moralitas bisa dipahami dalam kerangka alam (nature) vs pengalaman (nurture). Jawaban pertama, nativisme, mementingkan nature dan menyatakan bahwa moralitas itu bawaan. Manusia sudah punya moralitas dari “sono-nya”. Jawaban ini punya varian religius dan ilmiah. Varian religiusnya, nilai-nilai moral adalah anugerah dari Tuhan, satu paket dengan berbagai sifat dan karakteristik bawaan lainnya. Varian ilmiahnya, proses evolusi jutaan tahun telah membekali manusia dengan intuisi-intuisi moral yang penting untuk keberlangsungan hidup.
Jawaban nativisme sulit menjelaskan mengapa nilai-nilai moral kerap berbeda antar kelompok budaya. Perilaku yang dianggap tak bermoral oleh satu budaya kadang dianggap boleh-boleh saja, atau bahkan terpuji, di budaya lain. Ada banyak contohnya. Memanggil orang tua atau guru secara langsung dengan namanya dianggap tabu (melanggar moral) di banyak masyarakat Timur, namun biasa saja di masyarakat Barat. Mengonsumsi daging adalah hal biasa saja di banyak budaya, tapi dipandang tak bermoral di budaya-budaya tertentu. Hubungan seks di luar pernikahan adalah tindakan terlarang di banyak masyarakat, tapi merupakan hal biasa di masyarakat yang lain. Bekerja di luar rumah bagi perempuan dipandang sebagai hal mulia di sebagian masyarakat, tapi dicibir dan bahkan dilarang oleh masyarakat yang lain.
Keragaman nilai moral ini mendasari jawaban kedua tentang asal-usul moralitas, yakni empirisisme. Dalam pandangan ini, moralitas berasal dari lingungan, atau lebih tepatnya, dari norma sosial yang diwariskan pada anak-anak melalui proses akulturasi. Kita mewarisi nilai-nilai moral dari apa yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat. Empirisisme menolak asumsi bahwa nilai moral bersifat bawaan lahir. Salah satu implikasi dari empirisisme adalah relativisme moral: tidak ada tatanan nilai moral yang lebih baik atau lebih buruk daripada yang lain.
Mendobrak Dikotomi Nature vs. Nurture
Baik nativisme maupun empirisisme moral, dalam bentuk murninya, merupakan pandangan kuno. Psikologi modern menawarkan jawaban ketiga, rasionalisme, yang mengatasi dikotomi palsu antara empirisisme dan nativisme. Peletak fondasi rasionalisme moral tak lain adalah Jean Piaget, ilmuwan biologi yang kemudian menjadi raksasa intelektual psikologi abad ke-20 melalui riset-risetnya tentang perkembangan kognitif anak.
Piaget menyatakan bahwa yang berubah ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja dan dewasa bukan sekedar bertambahnya pengetahuan (yang diperoleh dari lingkungan). Yang berubah adalah struktur kognisi itu sendiri, dari yang semula hanya bisa memroses informasi sensorik (indrawi), menjadi bisa memroses informasi yang semakin abstrak. Pola perubahan struktur kognisi ini bersifat universal: semua orang yang berkembang secara normal akan mengalami tahapan perkembangan yang sama, terlepas dari budaya dan lingkungannya. Dengan kata lain, template perkembangan kognitif manusia (atau setidaknya predisposisinya) bisa dianggap bersifat bawaan.
Piaget percaya bahwa struktur kognitif dasar yang kita miliki digunakan untuk bernalar bukan hanya tentang dunia fisik, tapi juga dunia sosial maupun moral. Dengan demikian, penalaran moral seharusnya mengikuti tahapan perkembangan kognitif yang ditemukan Piaget. Hipotesis kasarnya begini: pada masa anak-anak, penalaran moral anak seharusnya konkret dan tidak logis, namun menjadi abstrak dan lebih logis mulai masa remaja. Hipotesis Piagetian ini dieksplorasi secara ekstensif pada tahun 1960an oleh Lawrence Kohlberg, yang menciptakan cerita-cerita singkat untuk menilai penalaran moral.
Tiap cerita tersebut memuat dilema moral, yakni pertentangan antara dua prinsip moral. Salah satu dilema moral Kohlberg yang paling terkenal adalah cerita tentang lelaki bernama Heinz yang mencuri obat demi menyelamatkan nyawa istrinya. Cerita ini membenturkan nilai kepatuhan hukum dengan nilai kemanusiaan. [Dilema serupa tercermin pada kisah tragis Fidelis Sudewarto, lelaki asal Kalimantan yang menanam ganja untuk merawat istrinya yang menderita kanker.]
Analisis terhadap alasan responden dalam menilai benar-salahnya para tokoh cerita-cerita Kohlberg menunjukkan bahwa penalaran moral berjalan melalui tiga tahap utama: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Pada tahap pra-konvensional, penghakiman tentang benar dan salah dilakukan berdasar hukuman atau hadiah yang diterapkan oleh orang dewasa. Bila Heinz masuk penjara karena mencuri obat, maka Heinz pasti salah. Pada tahap konvensional (usia sekolah dasar), mulai muncul kesadaran bahwa aturan merupakan kesepakatan sosial. Salah dan benar dinilai berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Bila masyarakat di mana Heinz berada memaklumi pencurian yang dilakukan karena terpaksa, maka perbuatannya pun dipandang tidak melanggar moral.
Pada tahap pasca-konvensional (usia remaja), mulai bernalar tentang alasan yang melandasi aturan formal. Remaja yang berada pada tahap ini mulai mengembangkan prinsip-prinsip moral mereka sendiri untuk menilai apakah sebuah aturan itu adil, kapan otoritas perlu dipatuhi dan kapan boleh membangkang, dst.
Kohlberg tidak berhenti pada memaparkan tahapan perkembangan moral. Ia juga menulis tentang implikasi pedagogisnya. Karena moralitas adalah hasil dari penalaran individu, untuk menjadi matang secara moral, anak-anak perlu diberi banyak kesempatan untuk bermain peran dan berlatih melihat dari perspektif orang lain dalam situasi-situasi di mana ada pertentangan pendapat dan nilai moral. Bermain peran dan bertukar perspektif ini lebih mudah dilakukan dalam interaksi sesama anak, dan sangat sulit dilakukan dalam interaksi dengan orang dewasa. Perkembangan moral akan terhambat jika anak-anak hanya diminta mematuhi aturan dan memercayai begitu saja nilai-nilai moral yang dipegang oleh orangtua/masyarakatnya.
Intuisi moral
Metode penelitian Kohlberg mengandalkan kemampuan memberikan respon verbal (bahasa) dari para respondennya. Kemampuan bahasa ini bisa jadi variabel yang mengotori validitas simpulan Kohlberg: jangan-jangan tahapan perkembangan yang ditemukan sekedar mencerminkan pertumbuhan kosakata dan kemampuan menyusun kalimat, dan bukan peningkatan penalaran moral itu sendiri? Elliot Turiel, salah seorang murid Kohlberg, memodifikasi metode gurunya untuk mengecek kemungkinan tersebut.
Seperti Kohlberg, metode Turiel melibatkan cerita-cerita pendek, namun dengan pertanyaan yang bisa dijawab dengan “Ya/Tidak” oleh responden. Dalam salah satu cerita Turiel, seorang siswa pergi ke sekolah mengenakan pakaian bebas, padahal di sekolah tersebut siswa seharusnya menggunakan seragam. Responden kemudian ditanya, “Apakah yang dilakukan siswa itu benar?” Sebagian anak pada tahap pra-konvensional akan menjawab bahwa siswa itu salah. Responden kemudian diberi pertanyaan lanjutan: “Kalau hal itu terjadi di sekolah lain yang tidak mengharuskan siswa memakai seragam, apakah siswa itu tetap salah?” Responden biasanya menjawab bahwa hal itu menjadi boleh dilakukan. Dengan kata lain, responden pada rentang usia pra-konvensional ternyata sudah menyadari bahwa aturan merupakan konvensi sosial.
Yang lebih menarik adalah ternyata para responden Turiel memberi jawaban berbeda untuk kasus yang melibatkan pelanggaran norma kesejahteraan dan keadilan. Misalnya, Turiel menggunakan cerita siswa yang mendorong temannya sampai jatuh demi merebut ayunan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa tindakan itu salah, meski hal itu dilakukan di tempat yang aturannya membolehkan siswa saling dorong dan berebut mainan. Turiel menyimpulkan bahwa meski tidak bisa menjelaskan alasannya dengan baik, anak-anak sudah bisa membedakan antara aturan moral dengan aturan yang merupakan konvensi sosial. Bagi Turiel, ini meunjukkan bahwa anak-anak punya intuisi bawaan yang mereka gunakan untuk mengenali aturan moral (yang berbeda dari aturan sosial). Turiel menyebutkan dua intuisi moral bawaan, yakni keyakinan akan prinsip “dilarang menyakiti orang lain” dan prinsip “dilarang curang/berbuat tidak adil”.
Teori intuisi moral Turiel punya kesamaan dengan rasionalisme moral-nya Kohlberg. Keduanya menyatakan bahwa moralitas adalah hasil karya individu, buah dari penerapan sifat bawaan manusia pada pengalaman sehari-hari. Bedanya, pada Kohlberg, landasan moralitas adalah skema-skema kognitif yang memungkinkan anak mengonstruksi prinsip moralnya sendiri. Pada Turiel, landasannya adalah intuisi tentang keadilan dan pencegahan rasa sakit. Karena skema maupun intuisi moral bersifat universal, moralitas yang dihasilkan pun seharusnya universal, meski dengan corak atau perwujudan yang berbeda-beda antar budaya.
Apakah intuisi moral universal?
Jika Turiel benar, maka orang dari berbagai budaya akan menggunakan intuisi moral tentang keadilan dan pencegahan rasa sakit untuk menilai benar-salah sebuah tindakan. Asumsi inilah yang dikaji dan dikritik oleh Jonathan Haidt, salah satu peneliti psikologi moral paling berpengaruh saat ini. Haidt adalah sarjana filsafat yang kemudian menekuni studi psikologi. Di satu sisi, ia sebenarnya lebih sepakat dengan teori intuisi moral Turiel daripada teori penalaran moral Kohlberg. Di sisi lain, Haidt merasa bahwa dua intuisi moral yang diajukan Turiel mengandung bias kelas menengah-atas Barat.
Keraguan Haidt bersemi ketika ia mengambil mata kuliah psikologi kultural yang diasuh seorang antropolog brilian bernama Alan Fiske. Dalam kuliah itulah Haidt membaca beberapa karya etnografi yang menggambarkan sistem moral yang begitu asing bagi orang Barat. Sebuah suku di Papua Nugini, misalnya, punya aturan yang rumit tentang apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh lelaki dan perempuan. Anak lelaki yang beranjak dewasa di suku tersebut harus menghindari makanan apa pun yang menyerupai vagina (misalnya, makanan yang merah, berlendir, berasal dari lubang, atau berambut). Pantangan ini tidak menyangkut pertimbangan gizi atau kesehatan (misalnya, untuk menghindari makanan beracun). Juga tak ada hubungannya dengan pembagian sumberdaya antar individu atau kelompok. Dengan kata lain, pantangan itu tidak bisa dipahami dari intuisi moral pencegahan rasa sakit maupun intuisi keadilan. Meski absurd menurut kacamata orang luar, aturan tersebut digunakan sebagai standar untuk saling menilai moralitas anggota suku tersebut.
Dari contoh-contoh semacam itu, Haidt berhipotesis bahwa intuisi moral pasti lebih beragam daripada yang diajukan Turiel. Tiap budaya menekankan kombinasi intuisi yang berbeda, sehingga menghasilkan sistem moral yang berbeda pula. Untuk menguji hipotesisnya, Haidt membuat cerita-cerita “harmless taboo violations” (tindakan melanggar tabu, namun tidak menyakiti siapa pun) dan meminta responden untuk menilai apakah tokoh ceritanya bisa dianggap melanggar moral. Berikut contohnya (Haidt, 2012, hal 3):
“Sebuah keluarga memiliki seekor anjing peliharaan. Suatu hari, anjing itu mati tertabrak mobil di depan rumah. Salah satu anggota keluarga mengatakan bahwa daging anjing itu enak. Bangkai anjing peliharaan itu pun dipotong-potong, dimasak, dan dimakan bersama. Tidak ada orang yang melihat mereka melakukannya."
Berikut contoh cerita lain yang lebih menantang:
“Ada seorang lelaki yang setiap akhir pekan membeli ayam utuh di supermarket. Sesampai di rumah, ia menyetubuhi alias berhubungan seks dengan bangkai ayam tersebut. Setelah itu ia memasak dan menyantap ayam tersebut.”
Haidt membandingkan respon dari orang-orang kelas menengah atas di kota besar di Amerika, dengan orang-orang kelas bawah di kota yang sama, serta orang-orang dari sebuah desa di Brazil. Bila Turiel benar, maka tidak akan ada perbedaan mendasar antara respon berbagai kelompok tersebut. Semua akan mengatakan bahwa pelaku perbuatan dalam cerita-cerita itu menjijikkan karena melanggar norma kepantasan. Namun demikian, perbuatan itu tidak bisa dianggap salah secara moral karena tidak ada yang disakiti atau menjadi korban.
Data yang dikumpulkan Haidt menggugurkan asumsi universalitas Turiel. Ternyata, respon yang sejalan dengan prediksi Turiel hanya muncul pada orang-orang kelas menengah atas di kota besar di Amerika. Sebagian besar responden dari kelompok lainnya menyatakan bahwa perbuatan dalam cerita-cerita tersebut bukan hanya menjijikkan, tapi juga salah secara moral. Haidt menyimpulkan bahwa mereka menggunakan intuisi moral yang berbeda dari intuisi moral orang kelas menengah atas Barat.
Temuan ini membuka jalan bagi penelitian untuk memetakan intuisi-intuisi yang menjadi landasan nilai dan sistem moral berbagai budaya.
Penutup
Menurut Haidt, keragaman intuisi moral menjadi kunci untuk memahami bukan saja perbedaan antar budaya/bangsa, tapi juga antar kelompok ideologi/politik. Keragaman intuisi moral menjelaskan, misalnya saja, mengapa ada orang-orang Islam yang sangat terganggu dengan adanya restoran babi panggang di sebuah pasar, namun ada juga orang Islam yang tidak memersoalkannya. Seperti apa persisnya, saya belum bisa bercerita karena memang belum tamat membaca bukunya
 :)
:)